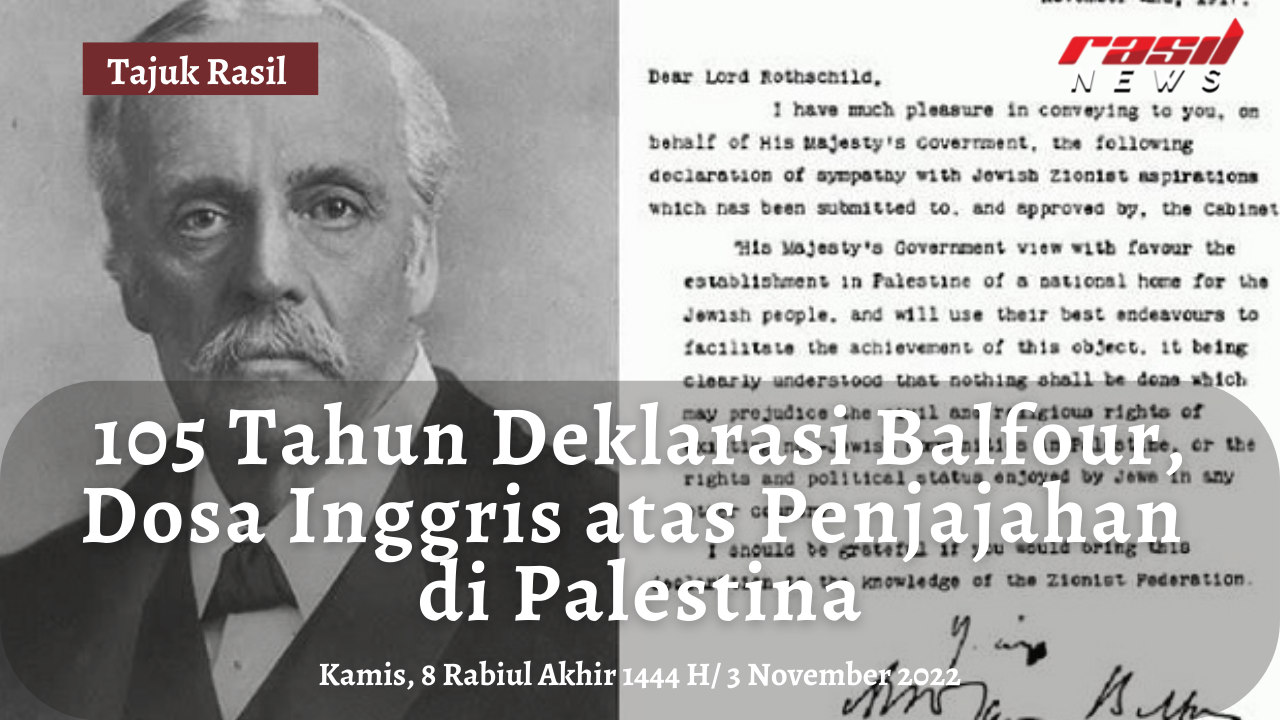Senin, 8 Rajab 1444 H/ 30 Januari 2023
Kolom Republika, Oleh: M. Nasir Djamil (Anggota Komisi Hukum DPR RI dari PKS)
Gegap gempita dan gelombang unjuk rasa kepala desa di Jakarta telah menyita perhatian publik. Padahal sebelumnya, tidak pernah ada ambisi kuasa dari pamong desa tersebut. Namun menjelang tahun politik, kepala desa ingin mendapat perhatian dengan cara menyampaikan keinginan mereka soal masa jabatannya. Ada apa dengan para kepala desa? Mengapa tiba-tiba mereka ingin kuasa diperpanjang hingga sembilan tahun dan dapat dipilih secara tiga periode? Adakah “udang dibalik peyek” dari tuntutan itu? Benarkah ada partai politik tertentu yang memolitisasi isu tersebut? Apakah tuntutan para kepala desa itu bagian dari “posisi tawar” mereka kepada Presiden Jokowi dan partai politik tertentu?
Desa memang sudah lama tertinggal dan terbelakang. Akhirnya nasib desa mulai terang benderang saat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disahkan oleh DPR dan Pemerintahan SBY saat itu. Sejak itu kedudukan kepala desa mulai diperhitungkan. Apalagi undang-undang tersebut juga mengatur soal dana desa untuk pembangunan desa. Jika sebelumnya jabatan kepala desa tidak “seksi”, pasca-UU Desa, perebutan jabatan kepala desa tidak pernah sepi dari sang calon. Bahkan tidak sedikit kepala desa menjadi “kaki-tangan” partai politik. Terutama desa yang memiliki jumlah pemilih besar. Sudah menjadi rahasia umum kalau parpol ikut membiayai calon kepala desa untuk kepentingan parpol. Dalam alam demokrasi realitas di atas sah-sah saja asal tidak menabrak aturan main yang diatur dalam peraturan perundangan.
Tidak dapat disangkal bahwa “euforia” di level desa itu tidak berkorelasi dengan kapasitas dan kompetensi kepala desa. Bahkan dari sisi usia banyak di antara mereka yang telah berumur 50 hingga 70 tahun. Begitu juga dengan kualitas pendidikan mereka. Ada yang masih tidak bisa baca tulis akibat minimnya tingkat pendidikan. Tak heran jika upaya Presiden untuk mensejahterakan desa dengan alokasi anggaran Rp 1 miliar pertahun berujung menjadi masalah hukum. Dan tidak sedikit juga yang kemudian harus mendekam di penjara. Akibatnya muncullah asumsi, jabatan kepala desa yang 6 tahun untuk satu periode saja membuat masyarakat desa resah dan pembangunan di desa melalui-salah satunya- melakui Badan Usaha Milik Desa mengalami stagnasi dan cenderung tidak merata.
Kepimpinan di semua level menghendaki regenerasi. Tidak terkecuali di desa. Permintaan 9 tahun untuk masa kepemimpinan kepala desa dan bisa ikut sampai tiga kali tentu saja menganggu sirkulasi dan regenerasi kepemimpinan di desa. Sebab bisa jadi ada kepala desa yang bisa berkuasa selama tiga periode atau 27 tahun lamanya. Tentu saja ini mirip dengan kekuasaan orde baru. Apapun alasan yang dikemukakan, keinginan di atas akan membuat demokrasi lokal di tingkat desa seperti berada di “leher botol”. Berkuasa terlalu lama bukan hanya tidak sehat, tapi berpotensi terjadinya korupsi. “Power attend corrupt”, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton, akan semakin banyak terjadi.
Lihat saja misalnya di sepanjang tahun 2022. Sebanyak 686 kepala desa di Indonesia, terlibat korupsi dana desa. KPK saat ini telah menangani sekitar 601 perkara korupsi yang melibatkan perangkat desa dengan 686 orang. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 sampai sekarang telah mencapai di angka Rp 468,5 triliun. Bukan jumlah yang sedikit. Angka kerugian negara tersebut masih merujuk kepada masa jabatan enam tahun dan satu periodesasi jabatan kepala desa. Dapat kita bayangkan apa yang terjadi jika masa jabatan menjadi sembilan tahun dan dapat dipilih selama tiga periode. Tentu potensi penyimpangan akan lebih besar lagi.
Bagi masa depan demokratisasi lokal, wacana yang disampaikan oleh organisasi kades tersebut akan berdampak buruk terhadap demokrasi dalam arti pengawasan oleh masyarakat. Rencana pemerintah dan DPR yang akan merevisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tentu harus disikapi secara kenegarawanan. Sebab jika hanya mengedepankan kepentingan sesaat yang bersifat sementara, tentu ini adalah kabar buruk bagi Indonesia. Justru yang perlu diperbaharui adalah mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana desa agar terhindar dari tangan-tangan kotor yang ingin menghancurkan perekonomian masyarakt desa.
Akhirnya, memang UU Tentang Desa harus direvisi. Tapi bukan untuk memperpanjang masa jabatan. Melainkan untuk memastikan agar dana desa haruslah berasal dari karsa masyarakat desa. Pengaturan dana desa yang “kaku” dan ditentukan penggunaannya oleh pusat tentu membuat desa tidak bisa berkembang. Sejumlah data dan fakta soal tersangkutnya kasus hukum terhadap kepala desa boleh jadi karena alokasi dana desa yang “dari atas” dan pengawasan serta pembinaan yang minimalis. Tidak ada suatu penelitian pun yang menemukan bahwa semakin lama memimpin akan membuat baik sebuah tempat yang di pimpin. Justru yang terjadi sebaliknya, akan bertambah buruk.
Kita berharap tuntutan perpanjangan usia jabatan kepala desa dan tiga periodesasi sebaiknya dihentikan. Mari fokus untuk membenahi manajemen administrasi dan keuangan dana desa. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepala desa. Tentu saja transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi “harga mati” yang tidak bisa dinegoisasikan. Kepada partai politik diharapkan tetap berkomitmen agar politisasi jabatan kepala desa akan berdampak buruk bagi masa depan demokrasi dan regenerasi kepemimpinan di tingkat desa. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengajak warga agar bisa berpartisipasi aktif dan konstruktif membangun desa.
Wallahu A’lam Bish-shawab